%%USERNAME%% %%ACCWORDS%% %%ONOFF%% |
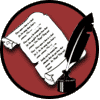 | No ratings.
The story about a lady that love to suit with black color demands of work and her life. |
| “Kau tak akan merasakan sakit bukan, Christine?” Pertanyaan yang begitu menyakitkan bagi ku. Ia memandangku begitu dalam. Seseorang yang dulu begitu lugu di hadapanku dan sekarang ia begitu tak berdaya. “Hey, cantik. Jangan pandangi dia begitu dalam.” Ben memeluk dan menciumku. “Apa kau sekarang punya perasaan kepadanya?” Ia tersenyum padaku sambil tangannya menjalani kedua lenganku. Bibirnya mencium leherku sehingga membuatku geli. “Kau bahkan tak pernah mengatakan cinta padaku.” Katanya lagi. “Benarkah?” Aku begitu menikmati caranya padaku. Begitu mencintaiku. “Lihatlah.” Ia kembali memandangku. “Seseorang yang begitu cantik ini selalu dapat tertawa dan tersenyum lepas bersamaku.” Ia kembali tersenyum. “Lihatlah dia, Sayang.” Ia melepaskanku dan berjalan ke arahnya. Dia begitu lemah dengan dikekang oleh dua orang besar. Ben berbicara padanya. “Apa selama ini kau merasa Christine dapat mencintaimu?” Ben mulai menjambak rambutnya. Sekarang rambutnya telah berlumuran darahnya sendiri. Aku teringat saat pertama kali aku datang ke depan rumah besar itu. Ia sedang mengurusi salah satu tanaman yang harus ia tanam dan ia menyeka keringat dari rambutnya. Entah mengapa ia seperti tahu akan kedatanganku. Ia lalu melihatku dan segera tersenyum padaku. “Good morning, Miss.” Ia seperti telah mengetahui siapa aku. Berapa lama aku tidak berada di bawah sinar matahari? Dan itu untuk pertama kalinya seseorang menyapa selamat pagi padaku. “Lihat aku, pemuda!” Ben sambil tertawa bengis membawa wajahnya berdekatan. “Apa kau tahu kalau kau hanya seonggok debu baginya? Hah!” Ia begitu gemetaran. Seluruh badannya penuh keringat, luka, bau darah, dan gemetar. Dan aku yang membuatnya sampai saat ini. “What are you doing, here?” Saat itu hari sedang hujan dan aku terdampar di sebuah kedai makanan. Saat aku sedang menikmati teh hangatku, ia datang dengan keretanya hendak membeli bunga di kedai itu. Kami saling berjumpa. “Well… I bought flowers.” Senangnya. “May I sit?” “Sure.” Ia mengajakku berbicara. “It’s a great time for a cup of tea.” Ia tetap menegakkan badannya di atas kursi. Tangan kanannya tetap menggenggam buket bunga itu. “Yes.” Jawabku. Tak ada pikiranku saat itu untuk membicarakan hal lain selain keanehan yang ia buat. Membeli bunga di hari hujan. “Is there someone sick?” “What?” “The flowers.” Aku menjelaskan. “ Are you going to see someone sick?” “Oh.” Ia tertawa. “No. It’s a present. A happy gift to someone.” “Birthday?” “No.” Jawabnya panjang. “But, you can guess.” “Someone you know has come arrived?” “No.” Ia mulai tertawa kecil. Senyumannya selalu memberikan gambaran akan keluguan di dalam dirinya yang sebenarnya. Seseorang dewasa yang memiliki keluguan di dalam dirinya. Aku hanya tak dapat memikirkan apapun dan aku mulai kembali meminum tehku. “So… you give up?” tanyanya. “I didn’t say it.” Jawabku. “Miss Rhymes. What do you think about the feel when the day is rainy?” Ia berbalik bertanya kepadaku. Pandangannya mulai melihat keluar kedai. Aku mencoba memandangi wajahnya. Ia tersenyum memandang semua itu. Aku mencoba melihat ke arah di mana ia melihat. “I’m thinking about wet things. Fog, dark, and cold.” Jawabku. “It’s different with me.” Ia membalasku. “I was thinking about a cup of warm tea, fireplace, warm cookies, and lights along the street.” “Those the good things.” Aku kembali menanyakan bunga itu. “What the correlation with the flowers?” “Do you think these flowers are lovely?” Ia membawa bunga itu ke atas meja. “I love white roses.” Jawabku. Aku mencoba memegang kelopak-kelopaknya. “It’s more than just a color. When black is empty, white is fulfill. Isn’t? Ia sudah lama memandangku. Saat aku menyadari pandangannya, ia kembali memandang bunga itu. “Yes, it is. The fulfill things. I want to tell her that even in the rainy days, there always some things that bring a fulfill parts. Good things as you said. Not always bad parts.” “So. It’s her?” Aku mencoba menerka siapakah perempuan itu. “Yes.” Ia tersenyum padaku. “It’s you.” Ben terus tertawa di depannya seperti orang gila. Ia tertawa akan sebuah ketidakberdayaan seseorang. “Sekarang aku biarkan kau memandang untuk terakhir kalinya!” Ia masih tertawa. “Wanita yang kau sangat cintai itu telah ada di hadapanmu.” Ben bergeser dari hadapanku dan sekarang kami dapat saling bertatapan. Wajahnya seperti begitu remuk dan lemah. Memar-memar. Mengapa setiap pria suka memakai baju dalam putih? Baju putih nya sekarang seperti kanvas dilumuti cat-cat tak beraturan. Lalu aku? “I never see you with except the black gown, Miss Rhymes.” Ia mengajakku jalan-jalan siang hari di taman kota. Kami membeli dua roti kecil untuk disantap bersama. Aku juga membawa keranjang rotanku berisi serbet dan sepasang gelas untuk botol red wine yang kubawa. “All things I believe. The bucket even black.” “It’s from the woods, I believe.” Ia tertawa mendengar jawabanku. Kami terduduk di salah satu bangku taman dan mulai menikmati roti dan red wine itu. “Why you never wear other colors?” “I love to.” Jawabku pelan. “I meet many colors everyday. I love them. But, this black color to remind me, who I am.” Aku mencoba kembali meminum red wine itu. “Who are you, then?” tanyanya. “The black swan?” “Excuse me?” Ia tersenyum. “Black hair, grey eyes, black ribbons, black shoes, black gloves, great skins, black earrings, soft red lips, and black gown. The prettiest darkness I ever enchanted of. Believe me.” Aku masih teringat perkataannya saat itu. Tapi aku tetap tak pernah mengerti alasannya untuk datang hingga sampai ke sini. “Christine.” Ben memanggilku. “Ya?” Tatapanku masih tetap kepadanya. “Mendekatlah.” Aku terdiam. “ Ayo.” “Baiklah.” Aku berjalan ke depannya. “Berikanlah sapaan terakhirmu kepada onggokan debumu ini yang terus mengotori kakimu. Biar setelah itu, aku akan membersihkannya untukmu.” Ia kembali tertawa Bengal. Nafasnya bahkan terdengar begitu berat namun cepat. Apakah ia sudah siap untuk mati? Ia tak mengucapkan kalimat apapun. Mungkinkah ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbicara. “Tak ada yang dapat kukatakan padanya. “Jawabku. Ben semakin keras tertawa. “Apa kau dengar itu, pemuda?” Kurasa Ben sudah sampai mengeluarkan air mata karena tertawanya sendiri. “Pujaan hatimu bahkan tidak ada kata-kata terakhir untuk kepergianmu. Begitu menyedihkan sekali dirimu.” Benarkah aku seperti yang dikatakan Ben? “Are you ever scared?” Saat itu aku sedang tertidur lemas di atas tempat tidurku dan ia sedang terduduk di kursi tepat di sebelah ranjang. Ia memegang tanganku. “No. I hate to be scared.” Ia tertawa. “Even things I pretty scared of, I can stand to always loving them.” “Maybe… you scared to hate.” Aku memberi kesimpulan. Ia lalu memandangku begitu dalam. “No ones ever told me that.” Katanya. Tangannya begitu dingin. Menyejukkan. “Yes. Maybe I scared to hate.” “Can you teach me how?” Aku masih ingat tatapannya penuh gundah. Begitu lama. Lalu ia mengecup tanganku yang ia genggam. Dia bilang iya. “Baiklah. “ Ben mulai menepuk tangannya. Aku segera ia dorong menjauh dari depannya dan ia kembali pada perkataannya. “Aku akan segera membersihkan debu di kakimu yang cantik, Christine.” Ben mulai membawanya ke atas dinding. Ia lalu menendang perutnya. Ben mencekik lehernya dengan satu tangan. Ia seperti tak berdaya. Ben mulai memukul wajahnya. Matanya berdarah dan memerah. Ben mulai kembali akan memukul ke daerah yang sama. Suaranya yang kesakitan terus menghujam telingaku. Seluruh arus darah di dalam tubuhku. Aku benci darah. Bau besi tua berkarat. Mengapa Tuhan memberikan bau darah seperti itu? Lalu mengapa Tuhan membiarkan tercipta manusia peminum darah? Mereka terlihat begitu menyedihkan dengan harus menelan begitu banyak besi-besi berkarat hanya untuk hidup. Bukan masalah karena itu. Sejak kecil aku punya penyakit darah sulit membeku. Sekali aku berdarah, darah itu akan terus mengalir jika tanpa perawatan terpusat padaku. Sejak kecil, aku diajarkan untuk terus takut akan darah. Waktu itu aku menyempatkan diriku mencoba untuk memakai baju tidak berwarna hitam. Sesuai dengan dress code pesta malam. Warna putih. Aku tak dapat membayangkan diriku dengan seluruh diriku berubah warna menjadi putih. Dan saat itu pikiranku hanyalah aku memakai ini hanyalah untuknya. Ia bilang aku seperti Putri Yoko, Dewi salju di Jepang. Tetap begitu misterius. Namun memikat. Kami menghabiskan waktu penuh warna. Tertawa, gembira, makan, berdansa. Dia pandai membuatku merasa nyaman. Sayangnya, saat itu ia hanya tahu kalau aku takut akan darah. Bukan penyakitku. Seseorang dari belakangku, menjatuhkan gelasnya di bawah kakiku. Belingnya begitu tinggi meloncat di udara dan hampir memotong sampai putus, urat nadi di pergelangan tanganku. Ia bilang aku disuruh tenang, tidak perlu melihat darahnya. Aku tak pernah muntah meski bau darah begitu menyengat seperti sampah metal. Hanya saja kemudian ia menyadari kalau darahku tidak berhenti. “I need a doctor! I need a doctor!” teriaknya pada orang-orang. Kurasa ia menyadari mengapa aku begitu takut memakai warna putih. Saat itu, seluruh darahku seperti menghujani pakaianku dan bercak-bercak darah itu seperti kain putih bekas pengoperasian atau kelahiran. Begitu mengerikan pasti pikiran orang-orang. Aku begitu lemah untuk menangisi kemalanganku. Dia memelukku begitu erat. “Hang on, Christine.” Untuk pertama kalinya. Ia begitu pandai, begitu lugu, dan selalu sopan dalam menjaga hubungan. Meski aku sudah tahu ia begitu mencoba mendekatiku dan membuatku menerimanya. Untuk pertama kalinya ia memanggil nama depanku. “We’re running out of time! Where’s the doctor!!!” “STOP!” teriakku seperti hasrat yang penuh sehingga seluruh badanku gemetar. Aku segera berlari dan menarik badan Ben hingga ia kulempar jauh. “AKH!” Ia terseret dan terpentok ke dinding seberang. Air mataku keluar di depannya. Aku menangis tersungkur gemetar di depannya. Ini adalah salahku mengatakan hal bodoh seperti itu. Aku menyadari alasannya. “I’m sorry…” Aku mencoba untuk menahan keguncanganku melihat dirinya yang begitu terluka parah di hadapanku. “Apa yang kau lakukan, Christine!” Suara Ben seperti hanya angin lalu bagiku meski terdengar menggelegar di belakangku. “Christine!” Ben terlihat marah padaku dan mulai mendatangiku. Terjatuh berlutut dan tak berdaya. Ia terbatuk-batuk dan batuknya mengeluarkan ludah bercampur darah di depanku. “Apa yang sedang kau perbuat!” suara Ben meninggi. “Hey.” Aku mencoba menemukan pandangan fokusnya. “Ini aku. Hey.” Akhirnya aku menemukan tatapannya. Ia berusaha bertahan di dalam keseimbangan badannya. “You… you don’t have to do that.” Aku segera melepaskan kedua sarung tanganku dan kupeluk dirinya begitu erat. “Kau dapat menaruh beban badanmu padaku. Apa kau sekarang merasa nyaman?” Aku tak pernah lagi takut akan darah. Aku percaya akan hal itu. “Aku tak percaya….” Aku dapat mendengar suara Ben dari belakang. “Apa yang telah diperbuatnya kepadamu?! Lepaskan pelukanmu!” Ia segera menarikku dengan kasar dan melepaskan dirinya. Ia lalu segera tersungkur tak berdaya. Aku memekik. Ben segera memandangku. “Apa kau sekarang mencintainya?” Aku tidak menjawab. “Air mata…” Ia menelusuri pipiku. “Taik!” Ia berteriak sambil menendang segala barang yang ada di sekitarnya. Aku memekik. “Aakh!” Ben mulai mengangkat senjatanya. “Ben…” Aku tahu apa yang sedang ia pegang. Ben tertawa aneh. “Kau tak bisa berbuat ini padaku, Christine!” Ia mulai menarik pelatuknya dengan cepat dan melepaskan satu tembakan tajam ke atas langit-langit. Aku kaget. “Ben!” teriakku. “Apa? Kau peduli? Hah?” Ia tertawa lagi. Sekarang ia menyenderkan ganggang pistolnya ke dahi. “Apa yang telah kulakukan…” ia berbicara sendiri. “Kau perlu tenang, Ben…” “TIDAK!” Ia kembali berteriak padaku. Aku tersentak dan ia melihatnya lalu tertawa. Ben melepaskanku dan segera menghujam pistolnya ke ia yang terbaring tak berdaya. “Aku tak pernah melihatnya berani membuat bajunya kotor dengan lumuran darah. Tak pernah kulihat ia berani melepaskan sarung tangannya dan memegang darah. Sebagai seseorang yang lebih dari seonggok debu… berani kau mengambil hatinya dariku!” Ia menekankan ke kepalanya. “Apa kau pernah mengatakan cinta padanya, Christine?” Ia beteriak kepadaku. “Tidak, Ben!” jawabku. Ben lalu tertawa. “Kau berbohong.” Katanya lagi. “Aku tak pernah berbohong padamu.” Seruku. “Tidak! Kau berbohong padaku. Apa kau mencintainya?” Suaranya meninggi. “Cepat jawab! Atau kau tidak akan pernah melihatnya bernafas lagi setelah kau mengatakannya.” “Apa?” Aku begitu tegang. Dan entah kenapa saat itu hatiku begitu marah berkecamuk dengan rasa penasaran dan penuh kesedihan. Aku… bisa merasakan semuanya. Semuanya. Air mataku semakin deras. “Jika selama ini aku dapat mempercayaimu, Ben, mengapa kau tidak mempercayaiku?” “Pertanyaan bodoh macam apa itu…” “Lepaskan dia…” Aku memandanginya begitu dalam. “Setiap darah yang kuteteskan untukmu adalah rasa cintaku padamu. Apa kau masih membutuhkan perkataan ketika aku sudah melakukannya? Sampai saat ini, aku masih mencintaimu. Apa kau sudah tak dapat mempercayaiku?” “DIAM!” “Akh!” Dia mendatangiku dan mencekikku dengan tangan yang memegang pistol. Pistol itu begitu dekat dengan wajahku. “Baik! Akan kubunuh dia!” Ia tertawa kecil. Ia melepaskan pedang kecil di pinggangnya. Pisau itu ia lempar ke arahnya. Aku tak melihat, namun kutahu pisau itu hanya meleset ke dinding di belakangnya. Tidak kena. Ben kembali tertawa kecil. “Apa… apa kau takut? Aku mungkin akan membunuhmu terlebih dulu.” Ia menghujam ujung pistol itu ke rahang bawahku. “Aku…” Jawabku pelan. “Menyukai apa yang kutakuti.” “ Apa?”Ia menatapku. “Apa… aku membuatmu takut?” “Bunuh aku, Ben. Aku tidak takut.” Aku menatapnya tajan. Ia kembali tertawa. Begitu keras. “Air mata… air mata… bagaimana seseorang dapat mengatakan kalau ia tidak takut namun terus menangis?” Ben kembali tertawa. “Aku benci wanita menangis.” Katanya. Ia benar-benar akan membunuhku. Dengan cepat ia menarik pelatuknya. Aku tidak takut. “I… “I know.” Bisikku. Pandanganku tetap memandangnya. Ia tersadar akan perkataanku. Saat itulah aku menjinjit. Kepalaku terangkat dengan cepat, kujambak rambutnya dan satu tanganku lagi dengan cepat mendorong pistol itu ke arah mulutnya. “As you said.” Satu tembakan ternyata cukup mengakhiri segalanya. Aku adalah seorang asisten pembunuh. Sejak kecil, saat itu aku pencuri makanan. Lalu Ben mendapatkanku. Ia dulu adalah asisten pembunuh. Pacarnya merawatku dan kami bersama-sama mempelajari cara membunuh lebih cepat. Aku maksudnya. Aku takut darah. Pacarnya mengajarkanku bagaimana membunuh seseorang tanpa harus melihat darahnya. Racun, tusukan dari belakang, malam hari, dan pakaian hitam. Darah mudah kering dan tak akan terlihat saat bajumu hitam. Kemudian, aku melihat Ben membunuh pacarnya itu. Aku tidak mengatakan apa-apa karena aku melihat pacarnya selingkuh dengan atasannya. Ben juga membunuh atasannya itu. Begitu halus dan begitu bersih pengerjaannya. Aku merasakan perasaan sedih Ben maka aku mulai mencintainya. Kami berdua menjadi pasangan pembunuh. Aku asisten pembunuh. Tak pernah ia memandangku begitu dalam. Semenjak kepergian pacarnya, ia menjadi suka gonta ganti kekasih. Dan kekasih-kekasihnya selalu berakhir dengan begitu mengenaskan. Mati. Sebagai asisten pembunuh, aku akan melakukan apa saja agar jejak pembunuhan yang Ben atau pun kulakukan terhapus. “Kau tahu, Christine.” Saat itu aku sedang mencuci kakinya dengan air hangat. “Aku tak akan bisa dibunuh oleh siapa pun. Percaya padaku.” Saat itu, kami berhasil membunuh seorang kaya raya. Uangnya kami ambil. Namun kami dikejar oleh polisi. Tak ada yang mengetahui kami untungnya. Para polisi itu menghujani begitu banyak biji peluru ke arah kami. Dengan cepat, kami mudah untuk menghindarinya dan malah Ben balik menembak dan ada beberapa yang mati. “Aku percaya, Ben.” “Kau… begitu mempercayaiku, Christine.” Katanya pelan. Ia lalu mengangkat wajahku. “Kau… begitu cantik.” Bukan salahku kalau aku begitu mencintainya kemudian. Hingga kami mendapat tugas besar. Siapapun yang memintanya kepada Ben, ia pasti benar-benar orang yang begitu besar. Dua orang yang harus dibunuh. Selama itu aku harus bisa masuk ke dalam rumahnya dengan mudah. Maka aku membeli rumah itu. Dan aku bertemu dengannya. Ben harus membunuh satunya lagi, yang berbeda tempat tinggal dengan targetku. Maka kami harus berpisah. Waktu begitu cepat dan kami mulai berkenalan. Ia mengira aku adalah seorang penulis muda kaya yang berusaha dapat bertemu untuk mewawancarai bahan yang ingin ditulis. Kukira ia hanyalah seorang pemuda biasa yang memiliki toko parfum dan sangat tahu akan segala bunga. Ternyata ia adalah anak dari target yang harus kubunuh. Pesta itu. Seharusnya aku dapat membunuh targetku. Lalu aku bertemu dengan Ben. Aku tidak menyadarinya sampai saat aku hendak dipertemukan dengan targetku. Ia melihatku. Ternyata Ben sudah menjadi rekan targetku. Tentu ia sudah membunuh targetnya dan mengambil semua kekuasaannya menjadi miliknya. “Father, she’s the woman I was talking about.” Kurasa targetku sudah menceritakan percakapan dengan anaknya itu kepada Ben. Ia begitu marah. Aku tahu tatapan marahnya yang begitu mudah ia samari dari wajahnya. Ia pergi. Aku tahu mungkin aku akan dibunuhnya. Aku berusaha tenang. Lalu seorang perempuan “seperti” menjatuhkan gelas minumnya di depanku. Aku tahu, dari jauh Ben menembakkan pelurunya untuk membunuhku. Ia selalu tahu cara menembak tanpa harus menyisakan pelurunya di tempat kejadian. Beling itu hampir membuatku kehabisan darah. Aku berhutang nyawa pada keluarga pemuda itu. Aku menceritakan semua rencana pembunuhan itu. Aku membantu mereka menangkap orang yang membayar Ben dan aku untuk membunuh. Ben tentu tidak kugunjing agar ia tidak tertangkap. Kukira semua telah berakhir dan sudah waktunya aku pergi. Namun semua itu berubah ketika pada akhirnya ia mengatakan cinta padaku. Ia cinta mati kepadaku. The prettiest darkness he ever enchanted of. “I was death, Sam.” Kalimat terakhirku sebelum aku menaiki kapalku. “The truth that I should to kill your father and I didn’t. That is the enough. We are dark and light. We can’t be together. “ “Christine…” Ia menangis. “You know the truth. The monster of love. Face when it’s murdered. Good bye, Sam. And good night.” Malam itu aku mengambil kapal berlayar malam hari. Sampai tempat Ben sudah sore hari di esoknya. Ia menyambutku. Ia bilang, ia memaafkan karena kebaikan hatiku kepada keluarga itu. Ia menanyakan bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Aku bilang iya. Ia menyimpulkan kalau aku begitu letih. Kami pun berhenti mmebunuh dan mulai berkeliling dunia. Menyenangkan. Sayangnya, aku tetap tak bisa menghentikan diriku untuk tidak memakai pakaian hitam. Ben membiarkanku memiliki privasi sendiri. Aku mulai menikmati hidup. Dan aku saat ini. Pasar malam. Seseorang berteriak padaku dari kejauhan. “Christine! Christine!” Ia mendatangiku dan memelukku begitu erat. “Sam…” Harum yang sama. Kehangatan badan yang sama. Ia masih sama seperti terakhir kutinggalkan. “I found you.” Katanya dengan semangat. “What are you doing?” “I never let this love die.” “Why?” “What?” “Why, Sam?” Hatiku yang menangis begitu terdalam. Bukan air mata. “I love you, Christine. We’re not dark and light. We are the black and the white.” Ia memegang tanganku dengan kedua tangannya. “When the black is empty, white fulfills the black. Let it be.” Seluruh badanku gemetaran.”I love you, Christine.” Ia memelukku. “Oh… Sam…” “I miss you so much.” “I… I miss you too.” Perasaan ini terlalu besar untuk kupertahankan. Aku tertawa di balik punggungnya. “It’s great to see you laugh again.” Katanya padaku. Aku hanya tersenyum. Aku memegang tangannya begitu erat. Tangannya yang begitu halus dan kuat. “Let’s go, Christine.” Ia menarikku untuk berjalan. “What?” “Let’s go with me.” Katanya begitu semangat. Kami menelusuri jalan pasar malam itu. Ia begitu ceria. “Where?” Aku menjadi ikut tertawa lepas. “The happy place!” Aku kembali tertawa. “All right.” Jawabku. “All right.” Ia segera mempercepat jalannya. Kami seperti berlari menuju cahaya kebahagiaan. “ I’m so happy that… Christine?” Ia menghadapkan wajahnya kepadaku “Why you stop? Christine, why you shaking…?” Ben mengira aku sampai saat ini tidak pernah menjalin hubungan dengan Sam. Namun, ia melihat Sam. Sam yang memegang tanganku begitu mesra. “What are you looking…” belum sempat ia berbalik, bawahan Ben sudah memukul kepalanya dan ia pingsan. “He’s disturbing us. A lot.” Bisiknya lalu mengajakku berjalan dan membawa kami ke tempat ini. Sam dihajar habis dan akhirnya. “Sam?” Aku yang telah meninggalkan badan Ben yang sudah tidak bernyawa segera kembali kepada Sam. “Do you…do you hear me?” Sam terlihat pingsan bagiku. “Uhuk!” Ia masih bernafas dan terbatuk. Aku senang melihatnya. “I’m sorry, Sam.” Aku menangis terisak. “I’m sorry.” ‘No…” Sam mulai menyeka air mataku. “No…” Dengan cepat, kami berdua diselamatkan oleh polisi. Sam diangkut lebih dahulu untuk segera mendapat perawatan secepatnya. Namun ia hampir tidak dapat melepaskan pegangannya dari tanganku. “You will be fine. I’ll go with you.” Kataku menenangkannya. “I love you.” Ia pun pergi keluar. “Miss. Miss Rhymes?” Seorang polisi menanyakan. Ia menyondorkan minuman hangat. “Thank you.” Aku segera meminumnya. Pihak medis segera merawa lebam-lebam kecil di leher dan mukaku. “Well… how he died? Who killed him?” Aku memandangi tubuh Ben yang begitu kaku. Sama seperti mayat-mayat yang telah kubunuh sebelumnya. “No. No ones can kill him.” “Really?” “Believe me. He killed himself.” |